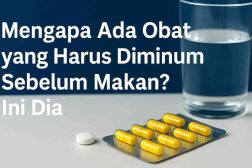Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan tinggi Taman Nasional Bukit Duabelas. Dari kejauhan terdengar suara burung enggang memecah keheningan, bersahut dengan langkah pelan seorang anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki di jalan setapak tanah merah. Ia membawa busur kecil di punggungnya—sebuah warisan sederhana dari ayahnya, simbol bahwa hidup di hutan bukan sekadar bertahan, tapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Di sinilah mereka hidup, jauh dari hiruk-pikuk kota dan deru kendaraan: Suku Anak Dalam, yang oleh sebagian orang disebut Orang Rimba. Mereka hidup selaras dengan hutan—menyatu dengan setiap desir angin, setiap jejak hewan, setiap getar kehidupan yang tumbuh di tanah Sumatra. Hutan bagi mereka bukan hanya rumah, tetapi juga guru, pelindung, dan bagian dari jati diri yang diwariskan turun-temurun.
Namun, dunia di luar sana terus berubah. Deru mesin pembuka lahan kian mendekat, menggusur hening yang dulu mereka kenal. Modernisasi datang tanpa mengetuk pintu, membawa sekolah, puskesmas, dan jalan aspal—namun juga membawa kehilangan yang tak kasat mata: hilangnya ruang hidup, bahasa, dan cara pandang dunia yang pernah begitu utuh.
Tulisan ini mencoba menelusuri jejak mereka: dari asal-usul dan kepercayaan, hingga perjuangan mempertahankan kehidupan di tengah tekanan zaman. Sebuah kisah tentang manusia dan alam yang saling terikat dalam keseimbangan rapuh—kisah yang mengingatkan kita bahwa di balik kemajuan, ada peradaban sunyi yang tengah berjuang untuk tidak dilupakan.
Kalau ada yang keliru tentang tulisan ini, mohon dikoreksi
Di antara kabut tebal dan lebatnya pepohonan di pedalaman Jambi, hidup sekelompok manusia yang menjaga warisan paling tua di Pulau Sumatra. Mereka adalah Suku Anak Dalam (SAD) — dikenal juga sebagai Orang Rimba — masyarakat adat yang masih mempertahankan cara hidup nenek moyang mereka di tengah arus modernisasi yang terus merangsek masuk.
Identitas dan Sebutan
Suku Anak Dalam merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang hidup di wilayah hutan pedalaman Pulau Sumatra, khususnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka juga dikenal dengan sebutan Orang Rimba, Orang Ulu, atau Suku Kubu.
Istilah “Suku Anak Dalam” sendiri berarti orang yang hidup di dalam hutan atau masyarakat yang masih tinggal di wilayah rimba. Sebutan ini menggambarkan gaya hidup mereka yang sangat bergantung pada alam dan lingkungan hutan tropis yang menjadi rumah utama mereka sejak ratusan tahun lalu.
Asal-Usul dan Sejarah
Asal-usul Suku Anak Dalam tidak dapat dipastikan secara tertulis, karena sebagian besar pengetahuan mengenai mereka diperoleh melalui tradisi lisan dan cerita turun-temurun.
Terdapat beberapa versi tentang asal-usul mereka.
Versi pertama menyebutkan bahwa nenek moyang Suku Anak Dalam berasal dari tempat yang disebut Maalau Sesat dan kemudian berpindah ke kawasan hutan Air Hitam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi.
Menurut penelitian antropologi Universitas Indonesia, sebagian besar ahli berpendapat bahwa mereka adalah keturunan bangsa Melayu Tua (Proto Melayu) yang datang dari Asia daratan sekitar 2.500–3.000 tahun lalu. Mereka memilih bertahan di hutan Sumatra, tidak berasimilasi dengan gelombang pendatang Melayu Muda, sehingga gaya hidupnya tetap terjaga hingga kini.
Versi lainnya menyatakan bahwa mereka merupakan keturunan masyarakat Minangkabau dari Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi, yang dibuktikan melalui kesamaan bahasa dan budaya.
Namun dalam legenda lisan mereka sendiri, nenek moyang Suku Anak Dalam disebut sebagai “Orang Tanah Serampas” — manusia pertama yang “tumbuh” dari bumi hutan, bukan datang dari mana pun. Dalam salah satu kutipan tokoh adat, Tumenggung Nggrip, ia berkata:
“Kami ini anak tanah, bukan orang datang. Hutan ini ibu kami, sungai bapak kami. Kalau hutan hilang, kami pun ikut mati.”
Dahulu, mereka dikenal sebagai masyarakat nomaden atau berpindah-pindah tempat. Pola hidup ini dikenal dengan istilah melangun, yaitu kebiasaan meninggalkan suatu tempat untuk sementara waktu setelah ada anggota keluarga yang meninggal dunia, dengan tujuan menghindari kesedihan dan malapetaka.
Peta Persebaran dan Wilayah Hidup
Suku Anak Dalam tersebar di beberapa wilayah pedalaman Pulau Sumatra, terutama:
- Provinsi Jambi: Kabupaten Sarolangun, Merangin, Batanghari, dan sekitarnya.
- Provinsi Sumatera Selatan: sebagian di Musi Rawas dan Banyuasin.
Mereka banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dua bentang alam yang menjadi “benteng terakhir” habitat Orang Rimba.
Lingkungan Hidup dan Mata Pencaharian
Suku Anak Dalam hidup di tengah hutan tropis dataran rendah dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Mereka mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berburu, memancing, meramu buah, madu, dan umbi-umbian.
Sebagian kelompok masih menjalani pola hidup semi-nomaden, berpindah tempat untuk mencari sumber makanan baru atau menghindari wilayah yang dianggap tidak aman. Hutan bagi mereka bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga sumber kehidupan dan bagian dari identitas budaya yang tidak terpisahkan.
Namun, pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur membuat wilayah tempat tinggal mereka semakin sempit. Akibatnya, banyak dari mereka yang kehilangan sumber makanan alami dan terpaksa berinteraksi lebih intens dengan masyarakat luar demi bertahan hidup.
Bahasa, Sistem Sosial, dan Budaya
Bahasa yang digunakan oleh Suku Anak Dalam termasuk dalam rumpun bahasa Melayu, yang merupakan bagian dari keluarga besar bahasa Austronesia. Dialek mereka memiliki kemiripan dengan bahasa daerah di wilayah Jambi dan sekitarnya.
Dalam sistem sosial, beberapa kelompok Suku Anak Dalam menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Kehidupan sosial mereka diatur oleh pemimpin adat yang disebut temenggung, yang bertugas memimpin, menjaga hukum adat, dan mengatur hubungan antaranggota kelompok.
Pakaian mereka sederhana, disesuaikan dengan kondisi lingkungan hutan. Laki-laki biasanya hanya mengenakan kain atau celana pendek yang terbuat dari bahan alami, sementara perempuan mengenakan kain panjang yang dililitkan di tubuh.
Dalam hal kepercayaan, sebagian besar Suku Anak Dalam masih menganut sistem kepercayaan animisme, yakni mempercayai adanya roh nenek moyang dan kekuatan alam. Mereka memiliki berbagai ritual adat yang berhubungan dengan kelahiran, kematian, pernikahan, dan berburu. Seiring dengan proses integrasi sosial, sebagian kecil sudah mulai memeluk agama resmi seperti Islam dan Kristen, terutama kelompok yang hidup di sekitar pemukiman masyarakat umum.
Sistem Kepercayaan
Suku Anak Dalam menganut animisme, mempercayai bahwa setiap unsur alam memiliki roh penjaga: pohon besar, sungai, bahkan batu keramat.
Mereka menghormati “dewo-dewo” (roh leluhur) dan melakukan ritual khusus sebelum berburu atau membuka ladang. Dalam kepercayaan mereka, melanggar pantang alam berarti mengundang bencana — keyakinan yang membuat mereka hidup selaras dengan ekosistem hutan.
Tantangan dan Permasalahan Kontemporer
Suku Anak Dalam menghadapi berbagai tantangan serius dalam mempertahankan keberlangsungan hidup dan budaya mereka. Salah satu tantangan utama adalah hilangnya lahan dan hutan adat akibat perluasan perkebunan dan proyek industri. Hutan yang dulunya menjadi sumber pangan dan tempat tinggal kini berubah menjadi lahan produksi, membuat mereka kehilangan akses terhadap ruang hidup tradisional.
Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Banyak anak-anak Suku Anak Dalam yang tidak bersekolah karena faktor lokasi yang terpencil dan kurangnya fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, proses modernisasi membawa dampak perubahan terhadap pola hidup dan nilai-nilai budaya. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan adat dan memilih hidup seperti masyarakat umum di luar hutan. Hal ini membuat sebagian budaya tradisional mereka terancam punah.
Namun, sebagian komunitas kini mulai beradaptasi. Mereka belajar menulis, berdagang madu hutan, dan ikut program konservasi. Meski begitu, seperti dikatakan Tumenggung Tarib, tokoh adat lain:
“Kami mau belajar dunia luar, tapi jangan suruh kami tinggalkan rimba. Di sinilah jiwa kami tinggal.”
Menurut berbagai penelitian, populasi Suku Anak Dalam saat ini diperkirakan hanya beberapa ribu jiwa yang tersebar di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Di Kabupaten Merangin, misalnya, jumlahnya sekitar 350 kepala keluarga dengan total 1.148 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Upaya Perlindungan dan Inklusi Sosial
Berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, telah berupaya untuk melindungi hak-hak Suku Anak Dalam. Beberapa organisasi seperti Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi aktif mendampingi mereka melalui program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta pelatihan ekonomi alternatif yang tidak merusak hutan.
Pendekatan budaya menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut. Misalnya melalui sistem sudung atau pondok sementara yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan komunitas Suku Anak Dalam di tempat mereka tinggal.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memberikan legalitas terhadap tanah adat dan memperkuat pengakuan hukum terhadap keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia. Upaya ini penting untuk mencegah konflik lahan dan memastikan hak mereka atas sumber daya alam tetap terjaga.
Pentingnya Mengenal Suku Anak Dalam
Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Mereka mencerminkan keragaman etnis, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa.
Mengetahui kehidupan dan perjuangan mereka bukan hanya bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Kehidupan mereka yang selaras dengan alam menjadi cerminan bagaimana manusia seharusnya menjaga keseimbangan dengan ekosistem.
Pemahaman tentang keberadaan Suku Anak Dalam juga membantu meningkatkan perhatian terhadap hak asasi masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, pendidikan, dan kesehatan. Dengan dukungan bersama, diharapkan mereka dapat mempertahankan jati diri sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.
Penutup
Suku Anak Dalam adalah potret nyata dari kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Mereka hidup selaras dengan alam, menjaga hutan, dan mempertahankan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun, perubahan zaman dan tekanan modernisasi membuat kehidupan mereka menghadapi tantangan besar.
Melalui kepedulian masyarakat, dukungan pemerintah, serta penghormatan terhadap adat dan lingkungan, masa depan Suku Anak Dalam dapat tetap terjaga. Pelestarian budaya mereka bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan luhur bangsa Indonesia.